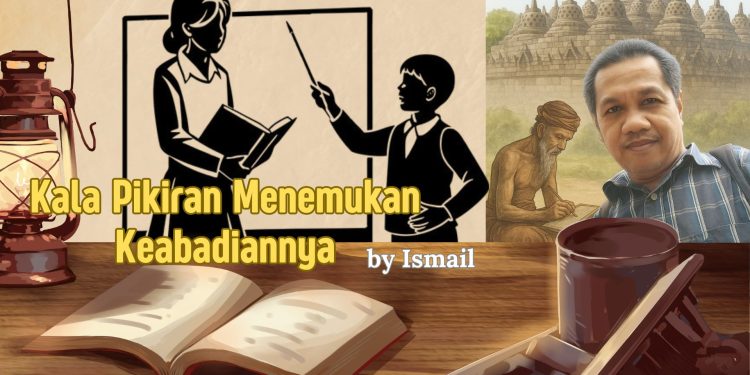Dari loh batu Mesopotamia hingga riuh rendah linimasa digital, tulisan tetap menjadi artefak paling akurat untuk merekam, menantang, dan mengabadikan gagasan. Ia adalah cermin zaman, sekaligus warisan peradaban.
(Ismail)
DI TENGAH belenggu fisik Pulau Buru yang terpencil, seorang sastrawan besar merangkai kata dalam benaknya. Tanpa kertas, tanpa pena. Pramoedya Ananta Toer, PAT, “menulis” dengan cara bercerita kepada kawan-kawan sesama tahanan politik. Ia mendiktekan semesta pemikiran, karakter, dan alur cerita yang kelak menjadi tetralogi mahakaryanya. Pikiran itu mendesak keluar, menolak untuk dipenjara bersama raganya. Kelak, ketika secarik kertas berhasil didapat, pikiran yang telah matang itu mengalir menjadi jejak abadi.
Kisah PAT adalah sebuah potret ekstrem namun akurat tentang esensi tulisan. Ia adalah manifestasi fisik dari proses berpikir. Sebuah upaya untuk menarik gagasan yang liar dan abstrak dari kepala, menjinakkannya dalam struktur kalimat, dan memberinya kehidupan di luar tempurung otak sang pemikir. Tanpa tulisan, sebuah pemikiran, sebagus apa pun, akan lenyap bersama hembusan napas terakhir pemiliknya.
Sejarah peradaban manusia pada dasarnya adalah tulisan. Lompatan kuantum dari tradisi lisan ke tradisi tulisan menandai era baru ketika pengetahuan tak lagi rapuh dan bergantung pada daya ingat satu generasi. Goresan paku di atas loh tanah liat di Sumeria sekitar 3.500 SM menjadi jejak pemikiran pertama yang merekam transaksi dagang, hukum, dan mitos. Kode Hammurabi tidak akan pernah menjadi pilar hukum dunia jika hanya diucapkan dari mulut ke mulut. Ia menjadi abadi karena terpahat di atas batu.
Tulisan adalah sebuah teknologi pengarsipan gagasan. Ia memungkinkan sebuah pemikiran untuk melintasi batas ruang dan waktu. Kita bisa “berdialog” dengan Plato tentang konsep negara ideal, menyelami kegelisahan Shakespeare tentang hakikat manusia, atau merasakan semangat perjuangan Kartini untuk emansipasi. Semua karena mereka meninggalkan jejak pemikiran dalam bentuk teks tertulis. Mereka telah tiada, namun pemikiran mereka terus hidup, memantik diskusi, dan menginspirasi generasi baru.
“Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan sampai saya menuliskannya,” ujar novelis Amerika, Joan Didion. Pernyataan ini menyingkap fungsi lain dari tulisan yang tak kalah vital: sebagai alat untuk menjernihkan pikiran. Proses menulis memaksa seseorang untuk mengorganisir ide-ide yang kacau, mencari hubungan sebab-akibat, dan membangun argumen yang koheren. Dalam keheningan di depan halaman kosong, baik itu layar laptop atau selembar buku catatan, kita bergulat dengan diri sendiri. Pikiran yang tadinya hanya sebatas firasat atau emosi, melalui tulisan, dipaksa untuk mempertanggungjawabkan dirinya dalam struktur logika.
Maka, tulisan juga menjadi alat perlawanan paling ampuh. Sejarah dipenuhi oleh pamflet, manuskrip, dan buku yang ditulis untuk menggugat kekuasaan. Tulisan-tulisan Martin Luther yang disebarkan mesin cetak Gutenberg mampu meruntuhkan hegemoni gereja yang telah bertahan berabad-abad. Manifesto politik yang disebar secara sembunyi-sembunyi oleh para pendiri bangsa ini membakar semangat revolusi. Penguasa bisa memenjarakan tubuh, membakar buku, namun jejak pemikiran yang telah tersebar akan selalu menemukan cara untuk tumbuh kembali.
Memasuki era digital, lanskap jejak pemikiran ini berubah drastis. Blog, utas di media sosial, hingga status singkat menjadi medium baru. Demokratisasi tulisan terjadi secara masif—setiap orang kini bisa menjadi “penerbit” gagasannya sendiri. Jejak pemikiran tak lagi monopoli kaum intelektual atau sastrawan di menara gading. Ia hadir setiap detik di linimasa kita, riuh rendah dan beragam.
Namun, di tengah banjir informasi dan kecepatan ini, sebuah pertanyaan relevan mengemuka: apakah jejak itu menjadi lebih dalam atau justru lebih dangkal? Di satu sisi, ide bisa menyebar lebih cepat dan luas dari sebelumnya. Di sisi lain, kultur “serba cepat” berisiko mengebiri kedalaman refleksi yang menjadi syarat lahirnya tulisan yang bernas.
Pada akhirnya, esensinya tetap sama. Entah itu dipahat di atas batu, ditulis dengan tinta di atas kertas, atau diketik pada layar gawai, setiap tulisan adalah sebuah kapsul waktu. Ia adalah artefak intelektual yang merekam pergulatan, pencerahan, kegelisahan, dan harapan seorang individu pada suatu titik waktu.
Membaca sebuah tulisan adalah upaya arkeologis untuk menggali kembali jejak pemikiran penulisnya. Sementara menulis adalah tindakan penuh sadar untuk meninggalkan jejak bagi masa depan. Sebuah warisan yang menegaskan bahwa kita pernah ada, pernah berpikir, dan pernah mencoba memaknai dunia. Dan jejak itu akan tetap ada, lama setelah kita semua tiada. (Di Kaki Bukit Menoreh).